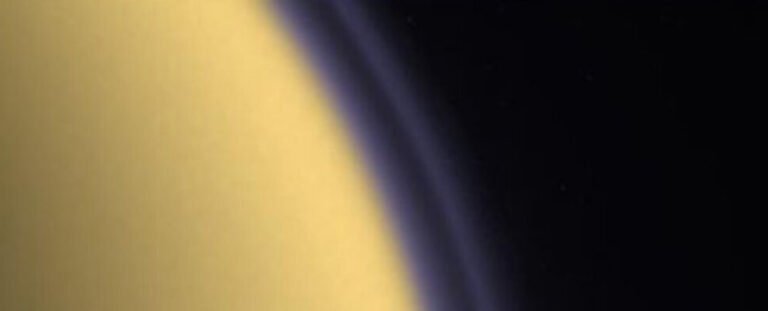Deir el-Balah, Jalur Gaza – Jehad Al-Assar meninggalkan tendanya di Deir el-Balah, Gaza tengah, pagi-pagi sekali untuk memulai perjalanan baru yang melelahkan demi mendapatkan makanan untuk keluarganya.
Tujuannya pada hari Rabu: titik distribusi bantuan di Rafah, di ujung selatan Gaza, yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung Amerika Serikat.
Jehad berjalan sejauh 10 km (6,2 mil) yang “melelahkan” untuk mencapai lokasi tersebut, didorong terutama oleh beban tanggung jawab terhadap istrinya yang sedang hamil dan dua putrinya yang kelaparan.
Dengan kelaparan yang meluas di seluruh Gaza, akibat langsung dari blokade Israel selama berbulan-bulan di wilayah tersebut, lokasi GHF adalah satu-satunya harapan Jehad.
Hal ini meskipun ada kontroversi seputar organisasi tersebut, yang bahkan ketuanya sendiri mengundurkan diri pada hari Minggu, dengan mengatakan bahwa GHF tidak dapat mematuhi “prinsip-prinsip kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan kemandirian kemanusiaan”.
Kurangnya pengalaman GHF dalam menangani distribusi bantuan disorot pada hari Selasa, ketika setidaknya tiga warga Palestina tewas dalam kekacauan yang mengelilingi upaya bantuan tersebut.
Namun di Gaza, orang-orang lapar dan putus asa. Jehad termasuk di antara mereka.
Setelah berjalan selama 90 menit, pria berusia 31 tahun itu mencapai gerbang besi pusat distribusi, bersama ribuan orang lainnya, sebelum tiba-tiba terbuka.
“Kerumunan berbondong-bondong masuk – ribuan orang. Tidak ada ketertiban sama sekali,” kata Jehad kepada Al Jazeera. “Orang-orang bergegas menuju halaman tempat tumpukan kotak bantuan dan masuk ke aula dalam, di mana ada lebih banyak persediaan.”
“Itu kacau – perjuangan yang nyata. Pria, wanita, anak-anak, semuanya berdesak-desakan, mendorong untuk mengambil apa pun yang bisa mereka dapatkan. Tidak ada antrean, tidak ada sistem – hanya kelaparan dan kekacauan,” tambah Jehad.
Di dalam aula, orang-orang mengambil apa pun yang bisa mereka bawa. “Siapa pun yang bisa mengangkat dua kotak mengambilnya. Gula dan minyak goreng menjadi prioritas. Mereka mengambil apa yang mereka inginkan dan bergegas keluar.”
“Tidak ada jejak kemanusiaan dalam apa yang terjadi,” katanya. “Aku hampir terinjak-injak kerumunan.”
Tidak jauh dari situ, pasukan asing bersenjata berdiri menyaksikan tanpa campur tangan. Jehad mengatakan dia mendekati salah satu dari mereka dan menghadapinya.
“Saya memberi tahu mereka, ‘Kalian tidak membantu – kalian mengawasi kelaparan. Kalian harus pergi. Kalian tidak dibutuhkan di sini.'”
Jehad hanya berhasil mendapatkan beberapa barang: kaleng tuna, kantong kecil gula, sedikit pasta, dan sebungkus biskuit yang berserakan di tanah. Dia membawanya dalam kantong plastik yang disampirkan di bahunya dan melakukan perjalanan panjang kembali ke rumah.
“Saya hanya mendapat sedikit. Saya takut untuk tinggal lebih lama dan terinjak-injak dalam kerumunan – tetapi saya harus membawa pulang sesuatu. Gadis-gadis saya perlu makan. Saya tidak punya pilihan,” katanya.
Ketika dia kembali ke tenda, putrinya menyambutnya dengan gembira – bahkan untuk sedikit yang dia bawa.
“Istri saya dan saya membagi makanan yang kami bawa pulang agar anak-anak dapat makan selama beberapa hari. Kami sering melewatkan makan. Anak-anak tidak dapat menahan ini… dan saya memikul tanggung jawab penuh untuk memberi mereka makan,” katanya.
Apokaliptik
Awad Abu Khalil juga berada di antara kerumunan yang putus asa pada hari Rabu. Pria berusia 23 tahun itu menggambarkan kerumunan yang bergegas mendapatkan makanan sebagai “apokaliptik”.
“Semua orang berlari. Itu kacau. Bantuan ditumpuk dan semua orang langsung menyerangnya, mengambil apa pun yang bisa mereka dapatkan.”
Awad mengatakan dia mendengar suara tembakan di kejauhan, kemungkinan menargetkan pemuda yang mencoba melewati rute yang ditentukan.
Dia mengungkapkan frustrasi mendalam terhadap staf. “Saya berharap staf Amerika mendistribusikan bantuan di meja, menyerahkan bagian masing-masing orang – bukan kegilaan ini.”
Gambar-gambar yang muncul pada hari Selasa dan Rabu telah menambah bahan bakar kritik internasional terhadap GHF, dengan perwakilan dari beberapa negara mengecam keputusan Israel untuk mencegah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi kemanusiaan internasional membawa bantuan ke Gaza.
Israel menghentikan masuknya bantuan ke Gaza pada awal Maret, saat gencatan senjata masih berlangsung. Sejak itu, Israel secara sepihak telah melanggar gencatan senjata, dan meningkatkan perangnya di Gaza, dengan jumlah korban tewas resmi kini lebih dari 54.000 warga Palestina.
“Kami dulu menerima bantuan dari badan-badan internasional dan PBB,” kata Jehad. “Itu disampaikan atas nama, dengan cara yang terorganisir – tanpa kekacauan, tanpa penghinaan.”
Pada akhir hari Rabu, Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan bahwa setidaknya 10 warga Palestina yang sangat membutuhkan bantuan telah dibunuh oleh pasukan Israel dalam 48 jam sebelumnya.
Penghinaan
Awad dan Jehad keduanya berhasil kembali ke rumah dengan membawa sedikit makanan.
Jehad mengatakan bahwa istri dan ibunya membuat roti dari pasta, merendamnya lalu menguleninya menjadi adonan. Istrinya menggunakan gula untuk membuat puding sederhana untuk anak-anak. Dia akan kembali pada hari Kamis, katanya.
Bahkan itu lebih baik daripada kebanyakan orang di Gaza.
Walaa Abu Sa’da memiliki tiga anak. Anak bungsunya baru berusia 10 bulan.
Wanita berusia 35 tahun itu tidak tahan melihat orang-orang kembali ke kamp pengungsian di al-Mawasi di Khan Younis membawa makanan sementara anak-anaknya kelaparan, jadi dia memutuskan untuk pergi ke Rafah sendirian.
“Saya bertengkar dengan suami saya yang menolak pergi karena takut pada tentara [Israel]. Saya bersumpah akan pergi sendiri,” kata Walaa kepada Al Jazeera.
Menitipkan anak-anaknya kepada saudara perempuannya, dia bergabung dengan kerumunan yang menuju ke lokasi distribusi.
“Anak-anak saya hampir kelaparan. Tidak ada susu, tidak ada makanan, bahkan susu formula bayi pun tidak. Mereka menangis siang dan malam, dan saya harus memohon sisa-sisa makanan dari tetangga,” katanya. “Jadi saya pergi, terlepas dari apa yang dipikirkan suami saya.”
Namun pada saat Walaa tiba di Rafah, sudah terlambat.
“Orang-orang berebut sisa-sisa yang sedikit. Beberapa membawa paket yang robek,” katanya.
Walaa meninggalkan lokasi distribusi dengan tangan kosong. Dalam perjalanan kembali, dia melihat seorang pria menjatuhkan sekantong tepung dari paketnya yang robek.
“Saya mengambilnya dan bertanya apakah saya bisa memilikinya,” katanya. “Dia berteriak, ‘Saya datang jauh-jauh dari Beit Lahiya di ujung utara [Gaza] untuk mendapatkan ini. Saya punya sembilan anak yang semuanya kelaparan. Maaf, saudari, saya tidak bisa memberikannya,’ dan dia pergi.
“Saya mengerti, tetapi kata-katanya menghancurkan saya. Saya menangis karena apa yang telah terjadi pada kami.”
Walaa menggambarkan pengalaman itu sangat menghina. Dia dipenuhi dengan rasa malu dan rendah diri.
“Saya menutupi wajah saya dengan syal sepanjang waktu. Saya tidak ingin siapa pun mengenali saya pergi mengambil paket makanan,” kata Walaa, yang berprofesi sebagai guru dengan gelar sarjana geografi.
Meskipun sedih, Walaa mengatakan dia akan melakukannya lagi jika diperlukan.
“Tidak ada martabat yang tersisa ketika anak-anakmu menangis karena lapar. Kami tidak akan memaafkan mereka yang membiarkan kami mencapai titik ini.”
(KoranPost)
Sumber: www.aljazeera.com
https://www.aljazeera.com/news/2025/5/29/not-aid-but-humiliation-a-desperate-search-for-food-in-gaza